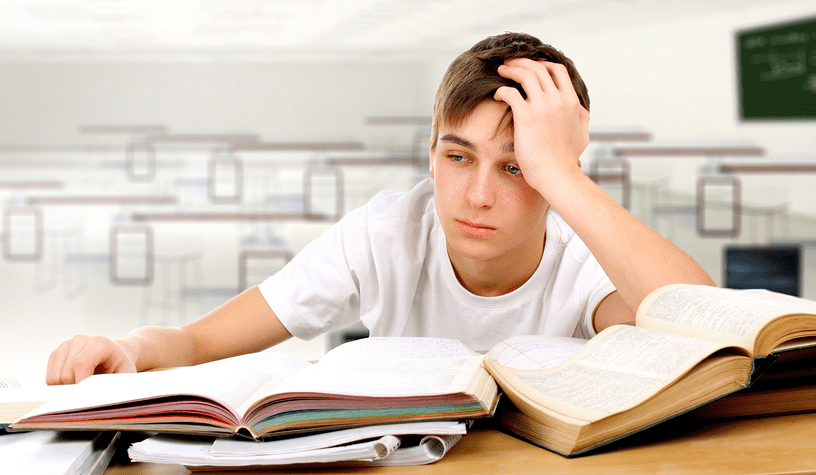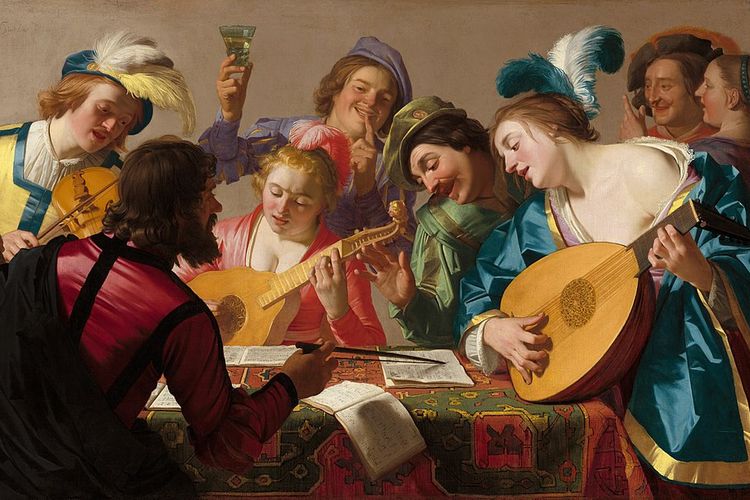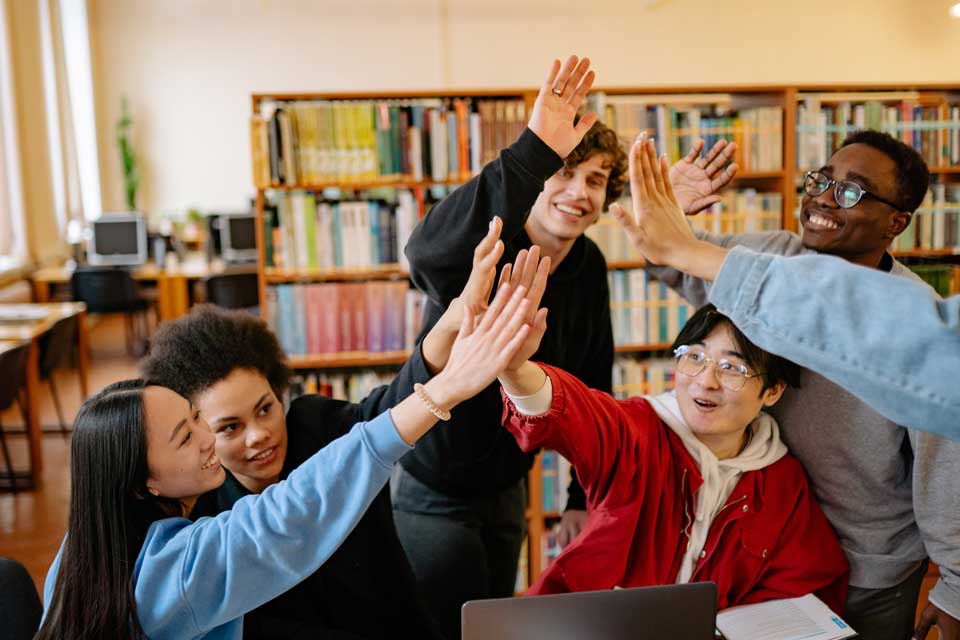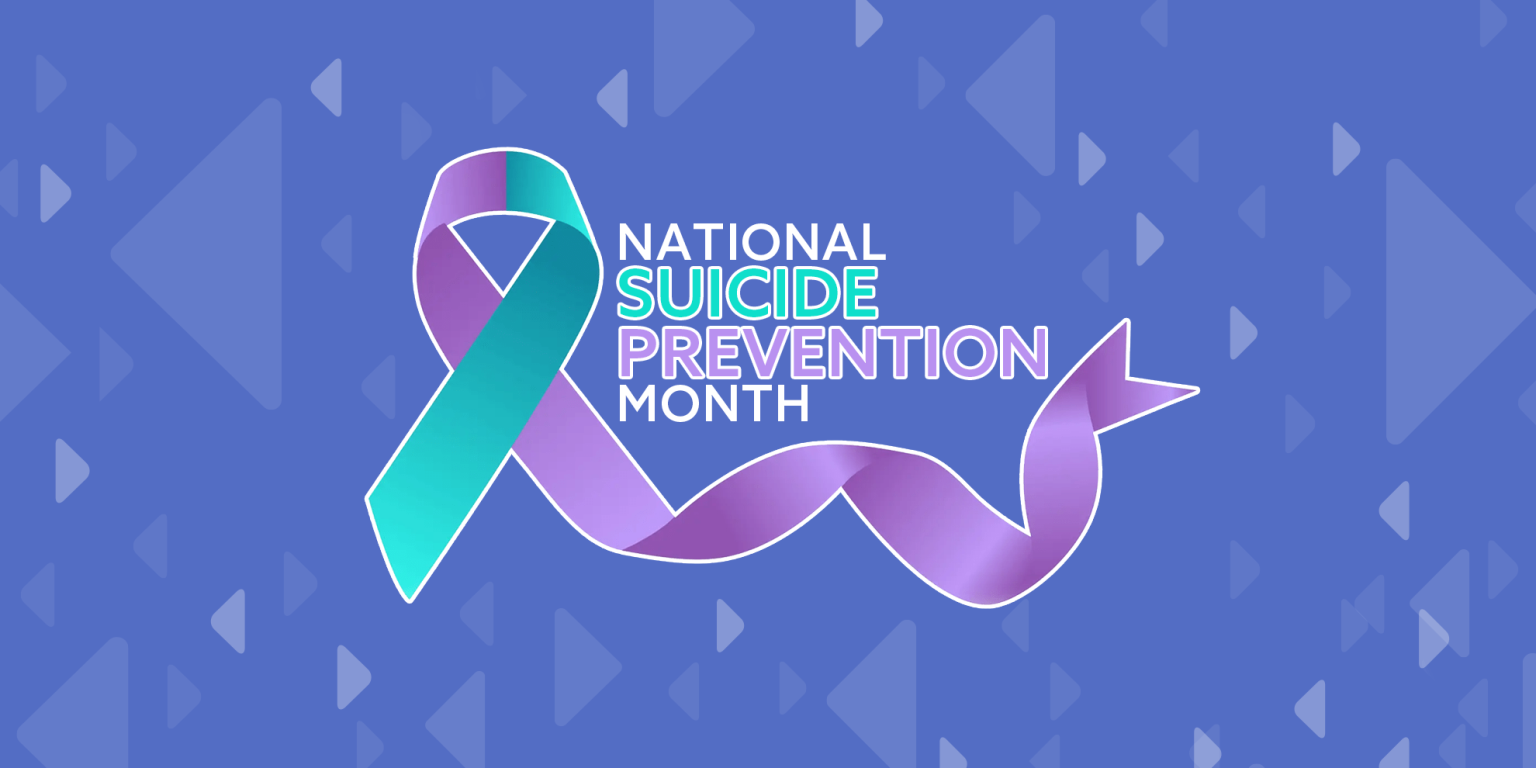Daily Hassles pada Anak dan Remaja: Tekanan Kecil yang Diam-Diam Menguras Mental
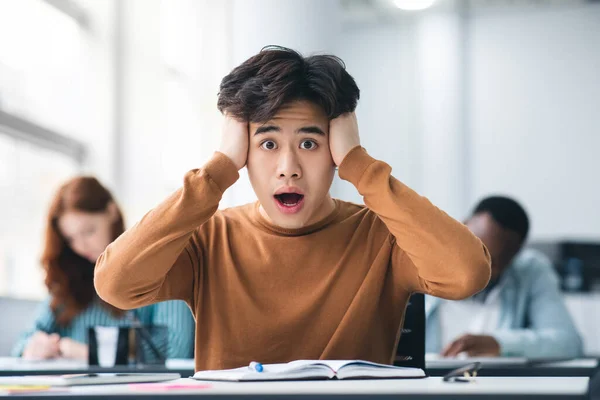
Prolite – Daily Hassles pada Anak dan Remaja: Tekanan Kecil yang Diam-Diam Menguras Mental
Pernah nggak sih kamu merasa hari berjalan biasa saja, tapi entah kenapa kepala rasanya berat dan mood gampang naik-turun? Bisa jadi kamu sedang menghadapi yang namanya daily hassles — gangguan kecil dalam hidup sehari-hari yang kelihatannya sepele, tapi kalau dibiarkan bisa menumpuk jadi stres yang besar.
Bagi anak-anak dan remaja, tekanan semacam ini sering datang tanpa disadari: dari PR yang menumpuk, teman yang tiba-tiba ngambek, sampai notifikasi media sosial yang bikin cemas.
Yuk, kita bahas lebih dalam tentang apa itu daily hassles, bagaimana dampaknya, dan cara menghadapinya biar hidup nggak terasa sesak setiap hari.
Apa Itu Daily Hassles?
Menurut para psikolog, daily hassles adalah gangguan kecil atau tekanan ringan yang terjadi berulang kali dalam kehidupan sehari-hari. Nggak selalu besar seperti trauma atau masalah keluarga, tapi justru datang dari hal-hal sederhana yang bikin capek mental kalau numpuk. Contohnya:
- Terlambat masuk sekolah karena macet.
- Bertengkar kecil dengan sahabat.
- Tugas sekolah yang menumpuk tanpa jeda.
- Kurang tidur karena scrolling media sosial terlalu malam.
- Merasa minder karena perbandingan di Instagram atau TikTok.
Mungkin terlihat sepele, tapi penelitian terbaru dari American Psychological Association (APA, 2024) menunjukkan bahwa akumulasi daily hassles bisa berdampak langsung pada meningkatnya kecemasan dan gejala depresi ringan pada remaja.
Tekanan kecil yang datang terus-menerus ini perlahan-lahan menguras energi emosional, apalagi kalau anak dan remaja belum punya strategi coping yang sehat.
Mengapa Rentan Pada Anak dan Remaja?
Usia anak dan remaja adalah masa transisi besar-besaran: dari perubahan fisik, pencarian identitas diri, hingga tekanan akademik dan sosial. Semua itu membuat sistem emosi mereka masih belajar beradaptasi.
Dalam survei global yang dirilis UNICEF (2025), sekitar 42% remaja mengaku sering merasa lelah secara emosional karena tekanan harian dari sekolah dan media sosial.
Beberapa faktor yang bikin mereka rentan antara lain:
- Pubertas dan hormon yang bikin emosi lebih fluktuatif.
- Tuntutan akademik yang makin tinggi.
- Tekanan sosial dari teman sebaya atau tren dunia maya.
- Kurangnya waktu istirahat karena padatnya jadwal dan paparan layar.
Bayangin aja: pagi sekolah, siang les, malam masih harus ngerjain tugas, dan di sela-selanya tetap harus tampil “baik-baik aja” di media sosial. Tekanan kecil seperti ini lama-lama bisa menimbulkan kelelahan mental kronis.
Dampak Daily Hassles pada Kesehatan Mental
Kalau dibiarkan terus, daily hassles bisa menimbulkan efek domino terhadap kesejahteraan psikologis anak dan remaja. Dampak yang sering muncul antara lain:
- Mood swing: gampang marah, sedih, atau kehilangan motivasi tanpa alasan jelas.
- Kesulitan fokus di kelas karena pikiran terlalu penuh.
- Penurunan performa akademik akibat stres ringan yang menumpuk.
- Gangguan tidur, seperti susah tidur atau tidur terlalu lama.
- Risiko munculnya kecemasan dan depresi ringan.
Riset terbaru dari Journal of Adolescent Health (2025) menemukan bahwa remaja yang mengalami lebih banyak daily hassles dalam seminggu cenderung menunjukkan kadar hormon kortisol (hormon stres) lebih tinggi dibanding mereka yang punya hari-hari lebih tenang. Jadi, bukan cuma soal “baper” — stres kecil benar-benar punya efek biologis nyata di tubuh.
Strategi Menghadapi Daily Hassles
Kabar baiknya, gangguan kecil ini bisa diatasi dengan langkah-langkah sederhana tapi konsisten. Berikut beberapa strategi yang bisa dilakukan anak, remaja, maupun orang tua:
- Evaluasi harian sederhana
Sebelum tidur, coba tulis 3 hal yang bikin stres hari itu dan 3 hal kecil yang berjalan baik. Dengan begitu, kamu belajar mengenali pemicu stres dan menyeimbangkannya dengan hal positif. - Komunikasi terbuka
Curhat ke teman, guru BK, atau keluarga bisa jadi cara melepas beban. Jangan nunggu masalahnya besar dulu untuk bicara. - Teknik koping ringan
Musik, journaling, olahraga ringan, atau sekadar jalan sore bisa bantu menurunkan ketegangan. - Kurangi paparan media sosial berlebihan
Coba “digital detox” kecil, misalnya nggak buka HP satu jam sebelum tidur. Otakmu butuh waktu istirahat dari notifikasi yang nggak ada habisnya. - Bangun rutinitas tidur yang sehat
Tidur cukup membantu tubuh memperbaiki sistem stres alami dan menjaga mood tetap stabil.
Dukungan dari Keluarga dan Sekolah
Orang tua dan guru punya peran besar untuk membantu anak dan remaja menghadapi tekanan kecil ini. Kuncinya ada di empati dan komunikasi. Daripada langsung menilai atau menyalahkan, coba ajak mereka ngobrol: “Apa sih yang bikin kamu capek hari ini?” Pertanyaan sederhana bisa membuka ruang aman untuk cerita.
Sekolah juga bisa berkontribusi dengan membuat program mental health awareness, seperti sesi mindfulness, mentoring, atau konseling ringan. Beberapa sekolah di Indonesia sudah mulai menerapkannya sejak 2024, dan hasilnya cukup positif: siswa lebih terbuka, lebih fokus belajar, dan suasana kelas jadi lebih suportif.
Saatnya Sadari dan Kendalikan Tekanan Kecil Itu
Daily hassles nggak akan pernah hilang sepenuhnya, tapi kita bisa belajar untuk nggak dikuasai olehnya. Hidup nggak harus sempurna setiap hari; yang penting kita tahu cara mengatur stres kecil biar nggak menumpuk.
Buat kamu yang masih sekolah atau remaja, coba mulai dari langkah kecil hari ini: kenali kapan kamu lelah, berhenti sebentar, dan kasih ruang buat diri sendiri.
Karena kesehatan mental bukan cuma soal besar kecilnya masalah, tapi soal seberapa sadar kita menjaga keseimbangan di tengah riuhnya kehidupan sehari-hari.