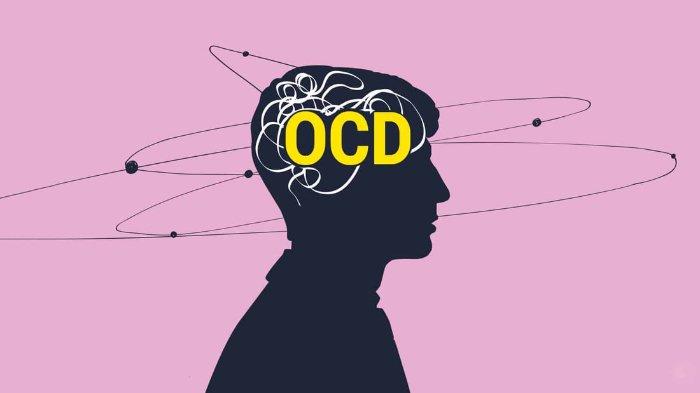Dysphoria pada Remaja: Ketika Pencarian Jati Diri Menjadi Tantangan Psikologis

Prolite – Dysphoria pada Remaja: Ketika Pencarian Jati Diri Menjadi Tantangan Psikologis
Masa remaja sering digambarkan sebagai masa pencarian jati diri. Namun, di tengah perubahan fisik, sosial, dan emosional yang begitu cepat, sebagian remaja mengalami perasaan tidak nyaman mendalam terhadap diri mereka sendiri, kondisi ini dikenal sebagai dysphoria.
Fenomena ini semakin sering dibicarakan, terutama dengan meningkatnya kesadaran tentang kesehatan mental dan identitas diri di media sosial. Tapi di sisi lain, juga muncul tantangan baru bagi remaja yang belum sepenuhnya siap menghadapi pergulatan batin tersebut.
Apa Itu Dysphoria dan Bagaimana Bentuknya?
Secara sederhana, dysphoria adalah kebalikan dari euphoria. Jika euphoria berarti perasaan bahagia yang berlebihan, maka dysphoria adalah perasaan tidak puas dan cenderung negatif terhadap diri sendiri atau keadaan tertentu. Bentuknya bisa beragam, di antaranya:
- Gender Dysphoria: perasaan tidak selaras antara identitas gender seseorang dengan jenis kelamin biologisnya.
- Body Dysphoria / Body Dysmorphic Disorder (BDD): ketidakpuasan ekstrem terhadap bentuk tubuh atau penampilan diri.
- Mood Dysphoria: perasaan murung, sedih, atau gelisah yang berlangsung lama tanpa sebab jelas.
Menurut data dari Journal of Adolescent Health (2025), kasus remaja yang melaporkan gejala dysphoria meningkat sekitar 23% dalam lima tahun terakhir, terutama di kalangan yang aktif menggunakan media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan digital juga punya peran besar dalam memperkuat persepsi negatif terhadap diri sendiri.
Kenapa Remaja Rentan Mengalami Dysphoria?
Remaja berada di fase unik — antara anak-anak dan dewasa — di mana banyak perubahan besar terjadi. Beberapa faktor utama yang membuat mereka lebih rentan terhadap dysphoria antara lain:
- Perubahan Fisik dan Hormon: Pubertas membawa perubahan besar yang kadang membuat remaja merasa asing dengan tubuhnya sendiri.
- Pencarian Identitas Diri: Mereka mulai mempertanyakan siapa diri mereka, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana ingin dilihat oleh dunia.
- Tekanan Teman Sebaya: Standar sosial di lingkungan sekolah dan pertemanan sering membuat remaja membandingkan diri mereka dengan orang lain.
- Pengaruh Media Sosial: Paparan terus-menerus terhadap citra tubuh sempurna, gaya hidup ideal, dan identitas gender yang beragam bisa memicu kebingungan atau rasa tidak cukup baik.
Sebuah survei oleh Pew Research Center (2024) menunjukkan bahwa 7 dari 10 remaja merasa media sosial membuat mereka lebih sadar — tetapi juga lebih tidak puas — terhadap penampilan dan identitas diri mereka.
Dampak Psikologis: Dari Stres hingga Isolasi Sosial
Dysphoria bukan sekadar rasa tidak puas biasa. Jika dibiarkan tanpa penanganan, kondisi ini bisa berdampak serius terhadap kesehatan mental remaja, seperti:
- Depresi dan Kecemasan: Perasaan tidak diterima atau tidak cocok dengan diri sendiri bisa menurunkan harga diri.
- Isolasi Sosial: Banyak remaja menarik diri karena takut dihakimi atau tidak dipahami.
- Bullying dan Diskriminasi: Terutama bagi remaja dengan gender dysphoria, risiko perundungan di sekolah cukup tinggi.
- Penurunan Prestasi Akademik: Kesulitan fokus dan stres emosional sering berdampak pada motivasi belajar.
Menurut WHO (2025), sekitar 35% remaja dengan dysphoria mengalami gejala depresi sedang hingga berat, dan sebagian besar belum mendapatkan dukungan profesional.
Dukungan yang Diperlukan: Dari Rumah, Sekolah, dan Profesional
Menghadapi dysphoria membutuhkan dukungan yang menyeluruh. Berikut beberapa bentuk dukungan yang penting:
- Konseling Psikologis: Terapi individual atau kelompok dapat membantu remaja memahami dan menerima dirinya.
- Peran Keluarga: Lingkungan rumah yang terbuka, empatik, dan tidak menghakimi menjadi faktor protektif utama.
- Sekolah yang Inklusif: Guru dan konselor sekolah perlu menciptakan ruang aman bagi siswa untuk mengekspresikan diri.
- Program Afirmasi Identitas: Terutama bagi remaja dengan gender dysphoria, afirmasi identitas membantu mereka merasa diakui dan dihargai.
- Akses ke Informasi yang Aman: Edukasi mengenai identitas, kesehatan mental, dan perubahan tubuh perlu disampaikan dengan bahasa yang ramah dan tidak menakut-nakuti.
Pemerintah Indonesia sendiri, melalui Kementerian Kesehatan (2025), sedang memperkuat program layanan kesehatan mental remaja di Puskesmas dengan menyediakan psikolog remaja dan ruang konseling aman.
Lingkungan dan Kebijakan yang Lebih Ramah Remaja
Masalah dysphoria tidak bisa diselesaikan hanya oleh individu atau keluarga. Lingkungan sosial dan kebijakan publik juga punya peran besar. Sekolah, lembaga kesehatan, dan komunitas perlu bekerja sama menciptakan sistem yang lebih inklusif dan edukatif.
Misalnya, beberapa sekolah di Jakarta dan Bandung mulai menerapkan pendidikan kesetaraan gender dan workshop kesehatan mental untuk siswa SMP dan SMA. Langkah seperti ini membantu mengurangi stigma dan meningkatkan empati antar siswa.
Dysphoria pada remaja bukanlah tanda kelemahan, melainkan sinyal bahwa mereka sedang berjuang memahami diri. Sebagai orang tua, pendidik, atau teman, kita bisa mulai dengan langkah sederhana: mendengarkan tanpa menghakimi. Kadang, dukungan emosional kecil bisa berarti besar bagi mereka yang sedang berjuang menemukan siapa dirinya.
Di era digital ini, penting bagi kita untuk menciptakan ruang aman — baik offline maupun online — di mana remaja bisa belajar mencintai diri apa adanya. Karena setiap remaja berhak untuk merasa nyaman menjadi dirinya sendiri.